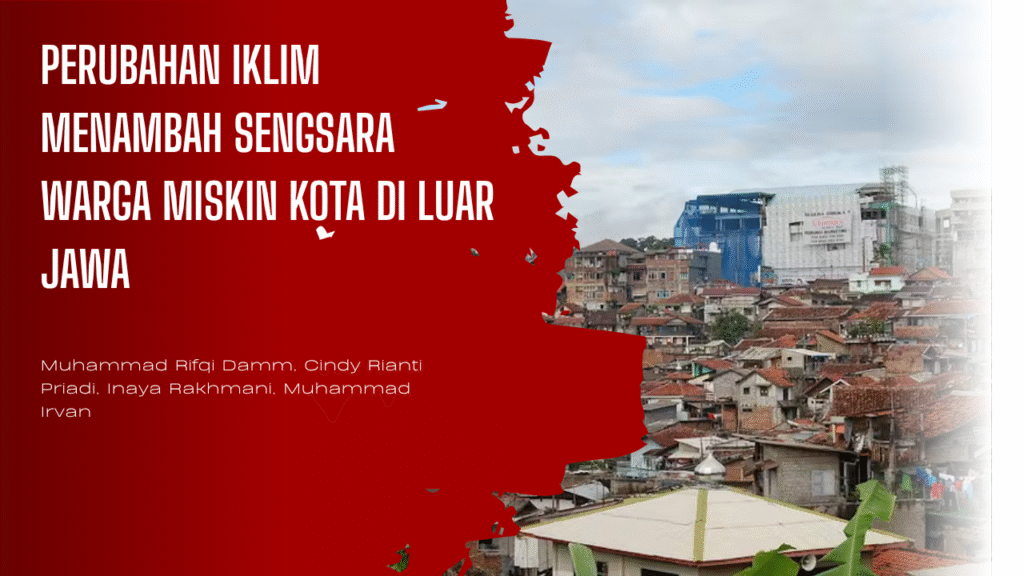Perubahan iklim menambah sengsara warga miskin kota di luar Jawa
Dampak Cuaca Ekstrem terhadap Masyarakat Miskin di Kota-Kota Indonesia
Perubahan iklim telah memicu peningkatan kejadian cuaca ekstrem di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banjir, kekeringan, dan gelombang panas kini menjadi ancaman yang semakin sering terjadi dan memengaruhi kehidupan jutaan orang. Pertengahan tahun 2023, dunia diwarnai berbagai bencana hidrometeorologi: banjir bandang merendam jalanan dan memaksa jutaan orang mengungsi di Amerika Serikat, Korea Selatan, Pakistan, dan Turki. Di Asia, periode monsun menelan lebih dari seratus korban jiwa, termasuk 22 orang di India utara akibat banjir mematikan. Indonesia pun tidak luput dari ancaman ini. Banjir besar di Kalimantan Tengah pada April 2023 berdampak pada 16 ribu jiwa, sementara kemarau panjang di Bima, Nusa Tenggara Barat, memperburuk krisis air bersih bagi warganya.
Penelitian ini dilakukan untuk memahami dampak cuaca ekstrem terhadap kawasan perkotaan, khususnya masyarakat miskin yang berada di garis depan risiko bencana. Studi dilakukan di tiga kota rawan banjir: Pontianak di Kalimantan Barat, Bima di Nusa Tenggara Barat, dan Manado di Sulawesi Utara. Melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan 57 narasumber yang mencakup pemerintah, tokoh masyarakat, aktivis organisasi sipil, dan pelaku usaha, serta analisis dokumen, penelitian ini menemukan bahwa masalah banjir, kekeringan, dan kelangkaan air di kota-kota tersebut sangat erat kaitannya dengan ketimpangan pembangunan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cuaca ekstrem berdampak pada semua lapisan masyarakat, namun warga miskin di perkotaan menjadi kelompok yang paling terdampak. Mereka umumnya tinggal di kawasan yang paling rawan banjir, padat penduduk, dan minim fasilitas air bersih. Akses terhadap jaringan PDAM seringkali tidak mereka miliki, meskipun letak permukiman cukup dekat dengan jalur distribusi air. Akibatnya, mereka harus mencari cara bertahan sendiri, seperti menggunakan sumur gali, memompa air tanah, menampung air hujan, dan membuat tandon air. Saat banjir datang, mereka memindahkan barang-barang ke tempat tinggi, memantau ketinggian air di parit atau sungai, serta memanfaatkan media digital untuk berbagi informasi darurat. Sayangnya, upaya ini bersifat reaktif dan belum menyentuh akar persoalan.
Di sisi lain, pembangunan kota yang pesat justru memicu ketimpangan baru. Kawasan pusat kota berkembang menjadi zona ekonomi dan perumahan mewah, lengkap dengan fasilitas modern, namun mendorong harga tanah dan biaya hidup melambung tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin. Sementara itu, perubahan tata guna lahan di wilayah sekitar kota, seperti alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, mengganggu keseimbangan siklus air. Ketika hujan deras datang, risiko banjir meningkat; saat kemarau, ketersediaan air bersih menjadi langka.
Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, pengelolaan air harus dirancang agar meningkatkan ketangguhan masyarakat, termasuk menghubungkan kembali warga dengan ekosistem air seperti sungai. Kedua, risiko perubahan iklim perlu dimasukkan dalam kebijakan dan perencanaan layanan air, serta pendanaan yang berkelanjutan untuk pencegahan bencana. Ketiga, pembangunan infrastruktur harus adaptif, dapat diperbarui, dan melibatkan partisipasi warga sejak tahap perencanaan.
Kesimpulannya, cuaca ekstrem akibat perubahan iklim adalah ancaman nyata yang memperparah ketimpangan di perkotaan. Tanpa upaya serius yang preventif, inklusif, dan terintegrasi dalam pengelolaan air, masyarakat miskin akan terus menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak bencana di masa depan.

Muhammad Rifqi Damm

Cindy Rianti Priadi

Inaya Rakhmani

Muhammad Irvan